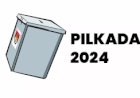Berita Populer
PENDAPAT
Menyambut Tahun Koperasi Internasional
Jurnalisme Konstruktif
Revolusi Indonesia dan Kaum Muda
NUSANTARA
POLITISIANA
WAWANCARA
Coblos Semua Paslon Boleh Dilakukan
 Peran militer dalam politik memang menjadi persoalan serius terutama di negara-negara yang berada pada tahap transisi seperti Indonesia. Apalagi pengalaman masa lalu, memang tak memberikan posisi yang cukup baik dalam melihat peranan politik militer.
Peran militer dalam politik memang menjadi persoalan serius terutama di negara-negara yang berada pada tahap transisi seperti Indonesia. Apalagi pengalaman masa lalu, memang tak memberikan posisi yang cukup baik dalam melihat peranan politik militer.
Sejarah kelam pemerintahan Orde Baru yang menempatkan posisi militer sebagai unsur dominan dalam perpolitikan nasional memang berakhir dengan berbagai kegagalan dan pengalaman pahit.
Memang faktornya bukan disebabkan hanya oleh peran dominan militer. Tapi toh, karena peran politik yang cenderung lebih mengemuka, akhirnya militer (TNI) menjadi sasaran tembak dari semua kegagalan pembangunan demokrasi di masa lalu.
Bagaimana sebaiknya memberikan posisi kepada militer atau TNI dalam kehidupan politik kebangsaan untuk masa depan? Saat ini telah diluncurkan RUU TNI. Beberapa kontroversi dan silang pendapat pun muncul mengiringi kehadiran RUU tentara ini.
Beberapa pengamat menilai, pasal 19 draf Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) justru merugikan institusi militer itu. Karena itu, pasal tersebut dan beberapa pasal lain harus segera dicabut dari draf RUU TNI sebelum dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Pendapat itu merupakan rangkuman dari sejumlah pengamat militer dan hukum yang bergabung dalam Koalisi untuk Demokrasi, di Jakarta, awal pekan ini. Di antaranya Kusnanto Anggoro, Ikrar Nusa Bhakti, Rizal Sukma, Todung Mulya Lubis, Munir, Syamsuddin Haris, dan M Fadjrul Falaakh.
Beberapa di antara mereka juga ikut terlibat dalam pembahasan draf RUU TNI tersebut. Mereka masuk dalam tim yang dibentuk Departemen Pertahanan (Dephan) sejak pertengahan 2002. Tim itu dibentuk berdasarkan surat keputusan (SK) Menteri Pertahanan untuk jangka waktu tiga bulan.
SK terakhir seharusnya sudah berakhir pada Februari 2003. Selama pembahasan draf RUU TNI itu, mereka menolak keras usulan yang tercantum pada Pasal 19.
Pasal tersebut menentukan, dalam keadaan mendesak di mana kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa terancam, Panglina dapat menggunakan kekuatan TNI sebagai langkah awal guna mencegah kerugian negara yang lebih besar.
Menurut Kusnanto, ada sejumlah kerugian bagi TNI akibat keberadaan Pasal 19 draf RUU TNI itu. Dengan pasal itu, TNI akan mengalami kesulitan dalam menafsirkannya, lebih mudah terbujuk oleh para politisi sipil untuk terlibat dalam politik, dan lalai dengan tugas utamanya dalam bidang pertahanan negara.
"Memang draf RUU ini belum menjadi RUU resmi. Untuk itu, masih ada peluang untuk mencabut pasal 19 itu dan membenahi pasal-pasal lainnya," katanya. Sesuai dengan UU No 3/2002 tentang Pertahanan Negara, tanggung jawab pengerahan pasukan TNI ada pada Presiden dengan persetujuan DPR. Namun, pada Pasal 19 draf RUU TNI, tanggung jawab itu berubah dan ada pada Panglima TNI.
Rizal menambahkan, RUU TNI seharusnya memberi perlindungan bagi TNI dari campur tangan politik. Namun, yang terjadi sekarang justru sebaliknya, TNI diberi peluang terlibat dalam suatu proses pengambilan keputusan. "Pengerahan pasukan itu seharusnya menjadi tanggung jawab politik. Pemegang tanggung jawab itu dipilih melalui proses pemilihan umum sehingga jika terjadi kesalahan mereka yang bertanggung jawab," tegasnya.
Namun, sambungnya, pasal 19 itu justru mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada TNI. Hal itu sangat merugikan TNI dan akan menimbulkan saling lempar tanggung jawab antara TNI dan pemerintah jika terjadi kesalahan.
Menurut Mulya, keberadaan pasal tersebut sangat berbahaya bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Sebab, pasal itu akan menjadi pintu masuk bagi militer untuk kembali mengambil peran dalam kehidupan berpolitik di Indonesia.
Bunyi pasal 19 itu, lanjut dia, sangat bertentangan dengan UU No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Bahkan, pasal itu juga bertentangan dengan Pasal 16 draf RUU TNI, yang menyebutkan, kewenangan pengerahan pasukan ada pada Presiden.
"Jika suatu UU tidak memiliki dasar konstitusi yang jelas, sudah bisa disebut batal demi hukum dan dapat menjadi objek judicial review. Artinya, jika RUU TNI itu lolos, akan menjadi suatu masalah yang serius," katanya.
Dia berpendapat, Indonesia sangat membutuhkan sebuah undang-undang yang mengatur eksistensi TNI namun isinya jangan diterima apa adanya. Untuk itu, harus ada kritikan yang tajam dari masyarakat terhadap RUU itu.
Sedangkan Munir mengemukakan, selama ini kritikan terhadap pasal 19 draf RUU TNI cenderung dianggap sebagai sikap traumatik terhadap sepak terjang militer. Penilaian seperti itu salah dan akan mengurangi bobot kritikan tersebut.
Sesuai agenda demokrasi dan reformasi, katanya, militer tidak lagi terlibat dalam kehidupan politik.
Untuk itu jabatan Panglima TNI, Kepala Badan Intelijen Nasional, dan Kapolri seharusnya tidak bisa disejajarkan dengan menteri. "Yang tersirat pada pasal 19 justru seperti itu, pejabat militer disamakan dengan kabinet, yakni dapat menentukan dan memberi penilaian terhadap situasi politik nasional," ungkapnya.
Menjadi pertanyaan sekarang, apakah Presiden Megawati Soekarnoputri mau meloloskan RUU TNI dengan tetap mencantumkan pasal 19 untuk dibahas di DPR. Jika yang terjadi seperti itu, berarti Presiden menghapus kewenangannya sendiri dalam mengerahkan pasukan TNI.
"Jika usulan seperti dalam pasal 19 itu lolos, saya khawatir akan komandan-komandan lain juga dianggap dapat menilai situasi di suatu daerah. Ini berbahaya," tukasnya.
Pengamat politik Syamsuddin Haris dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mempertanyakan, mengapa pasal itu muncul bertepatan dengan momentum Pemilihan Umum (Pemili) 2004. Dia mencermati, konteks pemilu menjadi suatu yang penting jika dikaitkan dengan pasal itu.
"Sangat mungkin terjadi kerusuhan massa pada pelaksanaan Pemilu 2004. Pasal itu memungkinkan adanya peluang bagi TNI untuk mengambil alih situasi keamanan," katanya.
Selain itu, lanjutnya, pasal tersebut menunjukkan TNI tidak percaya pada kebijakan pemerintahan sipil. Akibatnya, dari rumusan yang dibuatnya sendiri, TNI bisa saja membatalkan kebijakan yang sudah diputuskan oleh pemerintahan sipil.
Sadarestuwati: Kita Takkan Mampu Bersaing dengan China
Menjatuhkan Megawati, Mengapa Sulit?
© Copyright 2024, All Rights Reserved